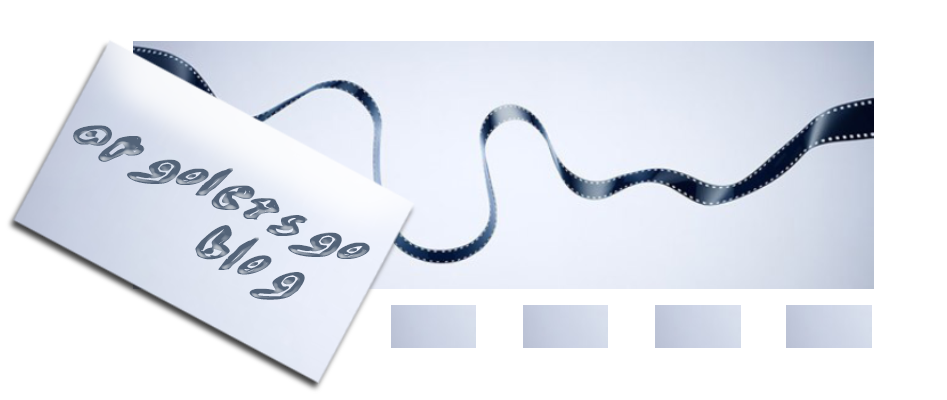“…atas bujukan setan - hasrat yang dijebak
jaman – kita belanja terus sampai mati…”
(efek rumah kaca – belanja terus sampai mati)
Keseharian hidup kita, terutama yang tinggal di daerah perkotaan seperti Jakarta, setiap detiknya tidak akan pernah lepas dari jeratan ‘shock therapy’ billboard-billboard, pamflet-pamflet, dan iklan konsumerisme.
Slogan-slogan ‘licik’ dengan wajah dan kata-kata yang manis, persuasif, dan penuh gairah terus ditayangkan, khususnya melalui media. Untuk itu siapapun tak akan menyadari bahwa dirinya sedang coba dipengaruhi oleh tanda dan citra yang menawarkan kebebasan, kenikmatan, dan kebahagiaan hidup yang sayangnya semu.
Itulah tanda-tanda post-modernisme. Suatu tanda zaman yang mengagungkan budaya massa. Indikasinya, konsumsi mengalahkan produksi, nilai tanda mengalahkan nilai guna dan nilai tukar. Contoh gampangnya, jika kita membeli produk import (apapun mereknya), bukan dilihat dari fungsinya tapi justru dari gengsinya (kecenderungan seperti ini banyak melanda kaum muda perkotaan). Dalam hal konsumsipun mereka cenderung memilih produk import ketimbang buatan lokal. Lebih memilih makan di McDonalds ketimbang di Mbok Berek. Padahal sajiannya hampir sama, yaitu dari ayam yang digoreng.
Semua ini mesti diakui adanya gempuran berbagai media yang semata-mata mengeruk keuntungan tanpa peduli sama sekali dampaknya adalah penyebab utamanya. Inilah kurun sejarah yang memuja bentuk dan penampakan ketimbang kekhususan, serta mengejar keuntungan ketimbang kemanfaatan/ kefungsian. Televisi, iklan, shopping mall, video game, kursus kecantikan, cat rambut, operasi plastik, adalah sederet ikon gaya hidup dan kosakata baru budaya massa. Dan budaya itu menyerang anak muda.
Budaya massa dipahami sebagai budaya popular yang diproduksi melalui teknik produksi massal dan diproduksi demi keuntungan. Budaya massa adalah budaya komersial. Budaya massa ditumbuhkan dari atas. Ia diproduksi oleh tenaga-tenaga teknis yang dipekerjakan oleh produsen. Khalayaknya adalah konsumer-konsumer pasif, dimana partisipasi mereka terbatas pada pilihan membeli atau tidak membeli.
Oleh sebab itu dalam realitas kebudayaan dewasa ini, tak ada lagi budaya tinggi, agung dan luhur, sebagaimana tak ada lagi budaya rendah atau pinggiran. Budaya tinggi kini telah berubah menjadi komoditi produk budaya yang dikomersialkan. Di bidang musik, dari situasi seperti ini bisa jadi sudah tidak ada lagi yang namanya genre musik tertentu lebih hebat dari genre musik yang lain. Kenapa demikian? Karena semuanya sudah jadi komoditas alias semuanya sudah harus dijual. Seperti yang terjadi dalam industri musik arus besar selama ini.
Semuanya sudah sama saja, sebab sudah jadi industri dan otomatis dijual secara massa alias murah meriah. Menurut AC Nielsen, 93% konsumen Indonesia termasuk recreational shoppers (pembelanja rekreasi). Mereka berbelanja bukan karena kebutuhan, tetapi lebih untuk kesenangan. Ini lebih parah dibandingkan dengan Amerika Serikat yang masyarakatnya terkenal konsumtif, hanya 68% saja konsumennya yang recreational shoppers.
Inilah paham konsumtivisme alias paham yang maunya mengkonsumsi saja.
Fenomena anak baru gede (abg) yang suka nongkrong di mall atau minum kopi di
Starbucks. Inginnya menggunakan merekmerek Louis Vuitton, Armani, Prada, Dunhill,
sampai dengan Ralp Lauren merupakan tanda nyata budaya konsumtif sudah menyerang.
Dan yang menjadi masalah adalah fenomena seperti ini tidak diimbangi pola hidup yang produktif dari masyarakatnya, alias tidak menghasilkan sesuatu.
Arus konsumerisme atau kecanduan belanja yang sifatnya emosional, bukan lagi rasional. Melalui iklan, kampanye, tayangan talk show, dan gempuran berbagai informasi melalui media massa, konsumen dirayu untuk mengkonsumsi lebih dan lebih banyak lagi. Dalam mekanisme komunikasi seperti ini, tak ada lagi pesan, tak ada lagi makna, kecuali semata-mata dorongan memikat untuk mengkonsumsi apa yang ditawarkan.
Menurut Baudrillard, konsumen adalah “Mayoritas yang diam”, yang pasif menerima segala apapun yang masuk ke dalam tubuh dan pikirannya, menelannya mentah-mentah tanpa pernah mampu merefleksikannya kembali dalam kehidupan yang sebenarnya. Dan inilah tanda-tanda masyarakat yang perlu dikhawatirkan. Apakah kita termasuk ke dalam mayoritas yang demikian?? (Di Udara #3 Juli '08)